Jakarta, Kabariku— Di sebuah ruang rapat di Jakarta, Jumat siang akhir Januari itu, pembaruan hukum pidana Indonesia dipertaruhkan.
Bukan lewat palu hakim atau dakwaan jaksa, melainkan melalui diskusi panjang tentang satu konsep yang selama ini sering dielu-elukan, tapi kerap dipraktikkan setengah hati yakni keadilan restoratif atau yang dikenal restorative justice.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar rapat persiapan kick-off meeting penguatan keadilan restoratif dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga riset hukum.
Di atas kertas, forum ini tampak teknokratis. Namun di baliknya, tersimpan pertanyaan besar, apakah keadilan restoratif akan benar-benar menjadi wajah baru penegakan hukum Indonesia, atau sekadar jargon reformasi?
Berlakunya KUHP dan KUHAP baru menandai babak baru hukum pidana nasional. Pemerintah kini dihadapkan pada pekerjaan rumah besar yakni, memastikan transisi hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh praktik sehari-hari penegakan hukum.
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Kumham Imipas, Robianto, menegaskan bahwa peran koordinatif kementeriannya menjadi krusial dalam mengawal agenda tersebut.
“Kemenko Kumham Imipas mengampu prioritas nasional berupa rekomendasi kebijakan melalui sinkronisasi dan koordinasi penguatan substansi hukum pidana yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif,” ujar Robianto, di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan, pengawalan itu berlandaskan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Landasan tersebut dilakukan dengan empat fokus utama antara lain: sinkronisasi Indeks Pembangunan Hukum, dukungan implementasi KUHP dan KUHAP baru, dukungan kebijakan prioritas Presiden, serta penguatan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun Robianto tak menutup mata terhadap tantangan di lapangan.
“Masih terdapat perbedaan konsep dan praktik penerapan keadilan restoratif. Karena itu, koordinasi lintas lembaga dan penyusunan standar nasional menjadi sangat penting,” katanya.
Kritik Masyarakat Sipil: Jangan Direduksi Jadi Solusi Lapas
Sementara itu, dari sisi masyarakat sipil menyampaikan kritik dengan nada yang lebih tajam. Arsil, peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menilai, keadilan restoratif di Indonesia kerap kehilangan ruh dasarnya.
“Keadilan restoratif itu bukan pengganti sistem pemidanaan. Ia seharusnya melengkapi, dengan fokus pada pemulihan relasi antara korban, pelaku, dan masyarakat,” ucap Arsil.
Menurutnya, dalam praktik pendekatan ini sering didorong oleh persoalan overcrowding lembaga pemasyarakatan, bukan oleh komitmen terhadap keadilan substantif.
“Kalau motivasinya hanya mengurangi kepadatan lapas, maka tujuan pemulihan akan sulit tercapai,” imbuhnya.
LeIP mendorong, pemerintah menetapkan target dan indikator yang jelas dalam regulasi, agar implementasi keadilan restoratif dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
Pandangan serupa datang dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu yang menilai, KUHP dan KUHAP baru sebenarnya telah membuka ruang yang cukup luas bagi keadilan restoratif.
“Peluangnya besar, tetapi tantangannya ada pada implementasi. Tanpa panduan konkret, konsep ini akan sulit diterjemahkan di lapangan,” tandas Erasmus.
Ia mendorong, pengembangan skema piloting dan community of practice antar lembaga, sekaligus menekankan peran strategis Kemenko Kumham Imipas sebagai koordinator.
“Harmonisasi cara kerja aparat penegak hukum itu kunci. Kalau masing-masing jalan sendiri, keadilan restoratif hanya akan jadi wacana,” tuturnya.
Risiko Tumpang Tindih dan Penyimpangan Prinsip
Sementara itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menyoroti dinamika regulasi keadilan restoratif yang kini berkembang dari sistem peradilan pidana anak ke pidana umum.
Perwakilan IJRS, Alexander Tanri mengingatkan, adanya risiko tumpang tindih aturan dan penyimpangan prinsip.
“Perlu kehati-hatian agar keadilan restoratif tidak disalahgunakan atau dijalankan tanpa standar yang memadai,” kata Alexander.
IJRS menekankan pentingnya keberadaan mediator tersertifikasi, pendamping bagi para pihak, serta praktik victim–offender dialogue yang terstruktur.
“Di sejumlah negara, dialog korban dan pelaku terbukti menurunkan residivisme. Tapi itu hanya berhasil jika dijalankan dengan standar profesional dan pengawasan ketat,” ujar Alexander.
Rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan spektakuler. Namun ia meninggalkan satu pesan kuat yakni, keberhasilan keadilan restoratif pasca KUHP dan KUHAP baru tidak ditentukan oleh teks undang-undang semata.
Ia bergantung pada komitmen lintas lembaga, kejelasan regulasi, dan keberanian untuk mengubah praktik lama yang selama ini berorientasi pada penghukuman.
Apakah keadilan restoratif akan menjadi wajah baru penegakan hukum Indonesia, atau hanya sekadar slogan reformasi? jawabannya akan diuji bukan di ruang rapat, melainkan di lapangan, pada perkara-perkara nyata yang menyentuh korban dan masyarakat.
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com




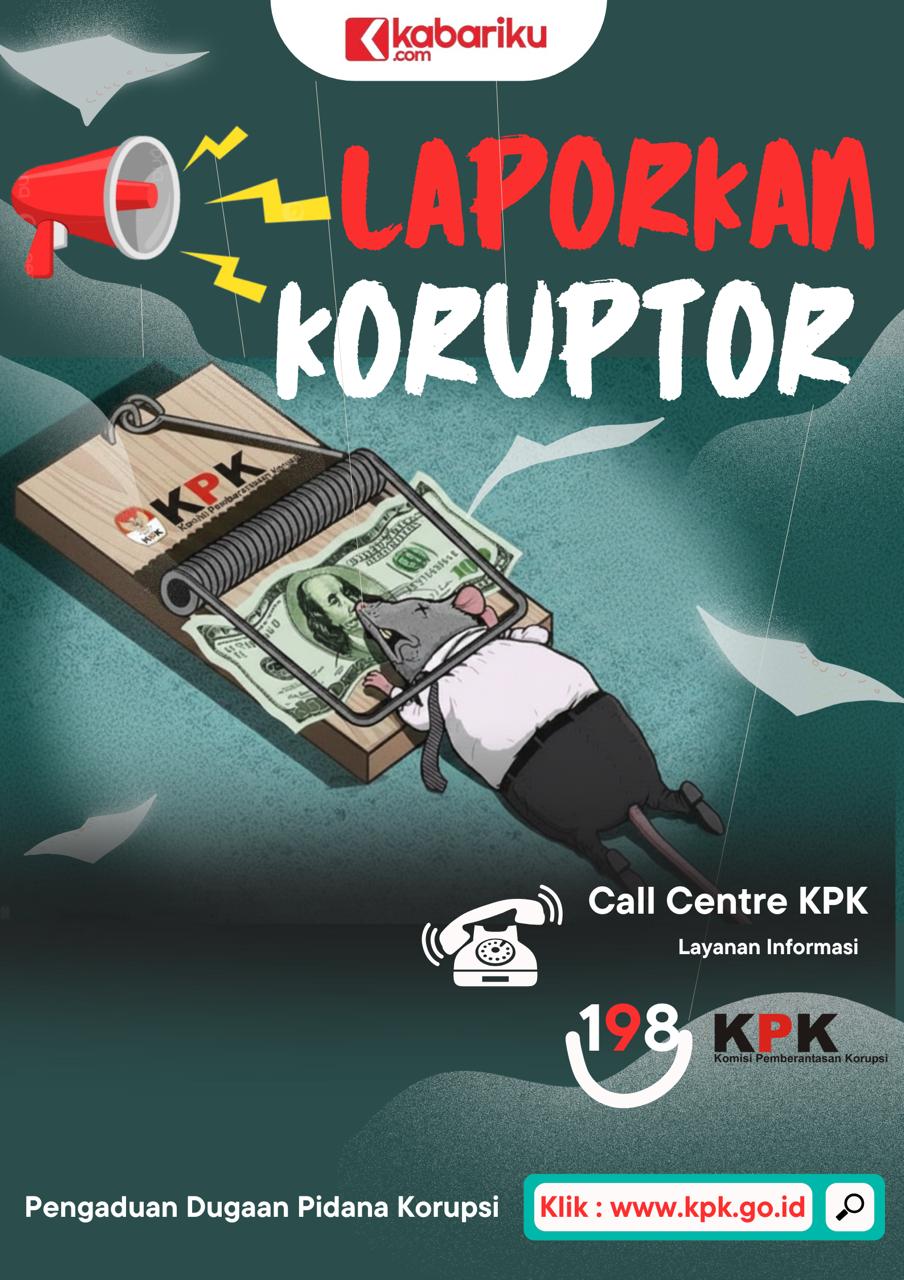












Discussion about this post