oleh :
Yaman Suryaman, SE., M.Si., Ph.D
Ketua Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB) Jawa Barat,
Ketua Lembaga Disaster Risk Reduction Centre Universitas Garut
Kabariku- Akhir-akhir ini sedang hangat menjadi pemberitaan nasional maupun di media sosial mengenai potensi bencana megatrust di Indonesia. Informasi ini secara menghebohkan bersumber dari lembaga resmi pemerintah yaitu BMKG yang akhir-akhir ini sering diliput oleh media nasional.
Padahal isu Megatrust ini sudah lama tetapi sekarang muncul lagi ke permukaan setelah terjadi gempa di Prefektur Miyazaki, jepang pada Kamis, 8 Agustus 2024 lalu yang berkekuatan magnitudo 7.1.
Secara khusus di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi dihantam megatrust ini karena kita memiliki potensi megatrust selat Sunda-Banten dan Megatrust Jawa Barat yang berpotensi memiliki kekuatan maksimum 8.8.
Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi potensi bencana ini sudah mengalami perkembangan signifikan, namun belum dapat dikatakan maksimal. Dikarenakan banyak hal yang masih menjadi PR bersama karena potensi bencana ini sudah di depan mata kita tinggal menunggu waktu terjadi.
Beberapa aspek mitigasi dan kesiapsiagaan sudah diterapkan dengan baik, namun ada juga aspek yang masih memerlukan perbaikan. Berikut adalah tinjauan mengenai seberapa maksimal upaya tersebut dalam mitigasi maupun kesiapsiagaannya.
Potensi megathrust di Selat Sunda-Banten dan Jawa Barat, ada beberapa langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang dapat dipelajari dari Jepang. Jepang telah lama menjadi contoh dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami, terutama setelah pengalaman mereka dengan gempa besar seperti Gempa Besar Kanto 1923 dan Gempa Besar Tohoku 2011. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dipertimbangkan:
1. Pemantauan dan Peringatan Dini
Jepang memiliki sistem pemantauan seismik yang sangat canggih, termasuk JMA (Japan Meteorological Agency) yang bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memantau aktivitas seismik.
Sistem ini mencakup sensor yang dipasang di laut dalam, yang dapat mendeteksi pergerakan dasar laut secara real-time, memberikan peringatan dini beberapa detik hingga menit sebelum gempa mencapai permukaan.
Sementara itu Indonesia meskipun sudah memiliki sistem peringatan dini yang telah mengalami peningkatan dengan pemasangan alat sensor gempa dan buoy tsunami.
BMKG secara rutin menguji dan memelihara sistem ini untuk memastikan fungsionalitasnya namun perlu penguatan dalam hal kecepatan dan jangkauan deteksi, serta memastikan masyarakat di wilayah rentan mendapatkan informasi ini dengan cepat dan dapat melakukan evakuasi tepat waktu.
Tidak semua daerah pesisir memiliki akses yang baik terhadap teknologi atau informasi yang dapat membantu mereka bereaksi cepat.
2. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat
Luasnya wilayah yang tersebar di Jawa Barat juga heterogen nya masyarakat yang menyulitkan proses kesiapsiagaan yang harus dilakukan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang harus segera dilakukan.
Hal ini harus dilakukan secara serius bukan hanya tindakan responsif hanya menanggapi berita yang sekarang sedang menjadi trend di media. Kita harus belajar dari negara Jepang dimana pendidikan bencana sudah menjadi bagian dari kurikulum sejak dini di Jepang.
Masyarakat secara rutin mengikuti simulasi evakuasi dan pelatihan lainnya. Sementara itu di Indonesia meski ada inisiatif untuk mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana masih dilakukan secara parsial dan belum terencana dengan baik.
Pemetaan wilayah yang harus menjadi prioritas untuk pendidikan dan pelatihan belum secara holistik dilakukan baik oleh BNPB maupun BPBD provinsi Jawa Barat dan BPBD yang ada di tiap-tiap kabupaten. Sementara itu kesadaran dan partisipasi masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil.
3. Infrastruktur Tahan Gempa
Jepang telah mengembangkan teknologi konstruksi yang tahan gempa, seperti bangunan dengan peredam seismik, dan pengaturan tata ruang yang mempertimbangkan risiko tsunami, termasuk tanggul laut dan sistem evakuasi vertikal.
Sedangkan di Indonesia dalam aspek bangunan dan infrastruktur perlu peningkatan standar bangunan dan infrastruktur, terutama di daerah yang berisiko tinggi terhadap gempa dan tsunami. Banyak infrastruktur di Indonesia belum dirancang untuk menahan gempa besar, sehingga rawan runtuh.
Proses perizinan bangunan belum dilakukan secara sungguh-sungguh karena ada beberapa faktor penyebabnya.
Pertama, tidak semua SDM pemerintah memahami pentingnya penegakan aturan untuk perizinan ini. Periznan bangunan dan infrastruktur belum memiliki rincian yang jelas mengenai spesifikasi maupun teknis dalam proses pembuatan bangunan dan infrastruktur ini.
Kedua, masyarakat yang masih berfikir bahwa ketatnya perizinan ini dianggap bahwa pemerintah menghambat terhadap pembangunan. Masyarakat jangan disalahkan jika mereka menganggap demikian karena kesadaran dan pemahaman mereka yang masih sangat kurang.
Ketiga, sebagian besar bangunan, terutama rumah-rumah penduduk di daerah pesisir, masih tidak memenuhi standar tahan gempa. Renovasi atau pembangunan ulang bangunan-bangunan ini memerlukan investasi yang besar, yang sering kali menjadi kendala
4. Manajemen Risiko dan Kebijakan
Kebijakan mitigasi risiko bencana di Jepang didukung oleh kerangka hukum yang kuat, termasuk Rencana Dasar Penanggulangan Bencana yang diperbarui secara berkala berdasarkan temuan terbaru.
Sementara itu meski Indonesia memiliki BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), tantangan kelembagaan dan birokrasi masih sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antar lembaga.
Apalagi fungsi BPBD di daerah yang semestinya sebagai instansi yang berbentuk “Badan” tetapi masih disamakan pola pengelolaannya dengan “Dinas” lain di daerah. Misalnya proses mutasi dan rotasi pegawai di BPBD.
Sangat sulit untuk memiliki pegawai yang profesional karena mereka dapat dirotasi atau mutasi dari atau ke dinas lain yang tentunya berbeda dengan BPBD. Seharusnya BPBD diperlakukan sebagaimana mestinya seperti instansi badan-badan lain seperti BIN ataupun BASARNAS.
Selain itu dalam langkah-langkah kesiapsiagaan implementasi jalur evakuasi di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti kondisi jalan yang buruk atau kurangnya fasilitas yang memadai di tempat pengungsian.
Selain itu, di beberapa wilayah, akses ke jalur evakuasi bisa terganggu oleh infrastruktur yang kurang baik. Lebih parahnya, jalur evakuasi belum didasarkan dari kajian komprehensif mengenai skenario proses evakuasi secara mandiri atau dengan melibatkan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan pasti berfikir evakuasi mandiri dengan menggunakan kendaraan masing-masing.
Tetapi hal ini bukan menjadi solusi terbaik ketika semua kendaraan turun ke jalan, yang akan terjadi adalah “bottleneck” atau kemacetan parah dan mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri.
5. Kolaborasi Riset dan Pengembangan Teknologi
Dalam bidang penelitian dan pengembangan IPTEK Jepang terus melakukan riset untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik gempa dan tsunami, termasuk melalui proyek seperti S-net yang memantau aktivitas seismik di Samudra Pasifik.
Sedangkan di Indonesia masih diperlukan kolaborasi lebih lanjut dengan memegang konsep pentahelix antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta untuk pengembangan riset terkait megathrust, termasuk pemanfaatan teknologi terbaru seperti sensor bawah laut dan pemodelan gempa.
6. Tantangan Kelembagaan dan Manajemen Bencana di Indonesia
Kelembagaan di Indonesia terkadang mengalami tumpang tindih fungsi antara pemerintah pusat dan daerah, yang memperlambat respons dan mitigasi.
Sementara itu manajemen bencana di Indonesia masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan minimnya integrasi data antar instansi membuat manajemen bencana tidak seefektif yang diharapkan.
Hal yang dapat dilakukan oleh Indonesia atau Jawa Barat secara khusus dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, mempercepat adopsi teknologi baru, dan meniru pendekatan partisipatif Jepang untuk kesiapsiagaan bencana yang lebih baik.
Meskipun sudah ada banyak langkah mitigasi yang dilakukan, kesiapsiagaan dalam menghadapi megathrust di Jawa Barat selatan belum bisa dianggap maksimal.
Beberapa area telah menunjukkan peningkatan, seperti sistem peringatan dini dan pelatihan masyarakat, tetapi masih ada banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur, pemerataan edukasi, dan kecepatan respons darurat.
Upaya untuk mencapai kesiapsiagaan yang maksimal membutuhkan investasi lebih lanjut, kolaborasi yang lebih baik antar lembaga, serta komitmen jangka panjang dari semua pihak terkait.***
Jawa Barat, 20 Agustus 2024
Referensi :
-Kanamori, H. (2006). Earthquake seismology. Treatise on Geophysics, 4, 593-608.
-Imamura, F., et al. (2012). Tsunami modelling manual. UNESCO/IOC Manuals and Guides No. 52, Paris.
-Widiyantoro, S., et al. (2020). The 2018 Sunda Strait Tsunami: Causes, Impacts, and Lessons Learned. Nature Communications.
-Meilano, I., et al. (2016). The Sunda Megathrust and the Potential for a Great Earthquake. Nature Geoscience.
Red/K.101
Baca Juga :
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com




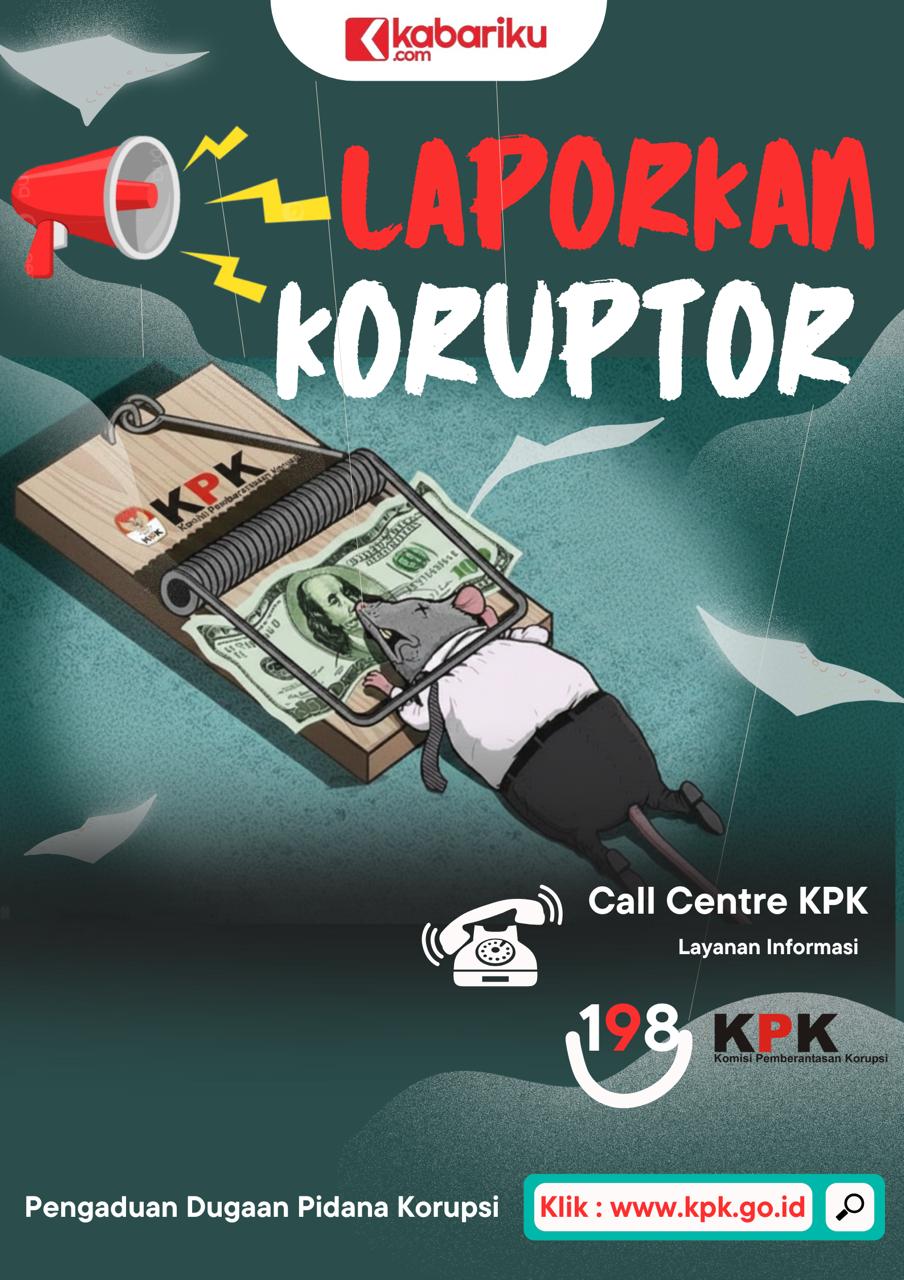















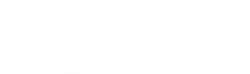
Discussion about this post