oleh :
Indra Kurniawan, S.H.,
Pengamat Politik Hukum Tata Negara
Kabariku- Menggali dasar hukum tentang Final dan mengikat (final and binding) pada setiap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi dialetika baru bagi sistem ketatanegaraan indonesia ditengah Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres/cawapres.
Dampak signifikan pada polarisasi politik pilpres semakin menguat, kekuatan elektoral pro Jokowi dengan majunya Gibran menjadi tantangan bagi kompetitor lainnya yang disikapi secara beragam baik secara hukum, politik dan sosiologis.
Lalu aktivitas diskusi menjadi dualisme serta tuduhan Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga dan sampai pendapat-pendapat mengenai konflik kepentingan dan dinasti Jokowi seakan menjadi perbincangan yang tidak ada hentinya.
Jika kita membaca secara seksama Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Lalu kemudian dalam penjelasannya bahwa Pasal 10 ayat (1): “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding)”.
Sudah sangat jelas, jika mendudukan pada ruang formil, maka dipastikan putusan ini mengikat dan dapat dijalankan serta tidak ada ruang dan upaya hukum lainnya untuk menguji kembali hasil putusan Mahkamah Konstitusi.
Akan tetapi apakah sebuah putusan final dan mengikat ini bersifat sempurna? atau
Apakah ada ruang lain yang mampu membuat putusan Mahkamah Konstitusi deligitimasi?
Tentu kita harus melakukan komparasi proper terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terutama pada ketentuan Pasal 17 yang dalam ayat (5) menyebutkan: Seorang Hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
Lalu ayat (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Dan pasal (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.
Jika memaknai Frasa ayat (6) adanya ketentuan Putusan dinyatakan Tidak Sah pada putusan Hakim jika memenuhi pelanggaran konflik kepentingan adalah sebuah perintah dan keadaan hukum baru, maka selanjutnya public official apa yang berhak menyatakan putusan MK tidak sah?
Dan atau apakah frasa putusan dinyatakan tidak sah ini adalah perintah Undang-Undang dalam kaidah batal demi hukum setelah ditemukan Pelanggarannya oleh Majelis Kehormatan Mahakamah Konstitusi (MKMK)?
Maka inilah dialetika baru dalam ketatanegaraan sistem hukum pengisian jabatan yang seharusnya dirumuskan lebih futuristik oleh pembentuk undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum (recht vaccum) pada aktivitas yudisial.
Tentu saja jika personifikasi jabatan Hakim MK menghasilan sebuah ilmu pengetahuan hukum dalam putusannya maka aspek keraguan akan selalu muncul, Skeptisme meminjam istilah Rene Descartes atau Wilhelm Lebniz dalam methodic doubt ( keraguan metodis) memungkinkan sebuah ilmu pengetahuan non matematis seperti dalam penciptaan hukum cenderung akan banyak memunculkan keraguan-keraguan, baik keraguan bagi pihak yang tidak diuntungkan ataupun memang keraguan itu muncul dari intelektulitas untuk pencarian posisi paling original dalam pengambilan keputusan-keputusan hukum yang berdampak pada masyarakat dan atau situasi politik tertentu.
Alexander Hamilton memberi definisi umum bahwa Judicial independence its the ability of courts and judges to perform their duties free of influence or control by other actors, whether governmental or private. The term is also used in a normative sense to refer to the kind of independence that courts and judges ought to possess.
Bahwa memang yang menjadi skeptis publik dalam putusan MK ini berkaitan dengan nilai-nilai independen hakim-hakim yang memiliki potensi konflik yang besar sehingga meskipun konsiderasi Hakim dalam original intens serta penafsiran kontekstual memiliki argumentasi yang kuat (strength of argument and justice) sepertinya belum mampu mereduksi penilaian publik tentang kentalnya keberpihakan.
Lalu kemudian final dan mengikat dalam sebuah putusan MK apakah masih memberi ruang untuk dinyatakan tidak sah atau batal, tentu norma Undang-Undang lain membolehkan menyatakan putusan tidak sah sepanjang memenuhi syarat pelanggaran yang ditentukan.
Maka jika pelanggaran itu sudah ditentukan oleh lembaga yang ditunjuk seperti MKMK telah menyatakan adanya misconduct dalam pelanggaran etik, maka kemudian MKMK ini akan meminta Mahkamah Konstitusi secara lembaga menyatakan putusan tidak sah untuk kemudian dilakukan kembali pemeriksaan ulang dengan susunan Majelis Hakim yang berbeda.***
Selasa, 7 November 2023
Red/K.101
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com




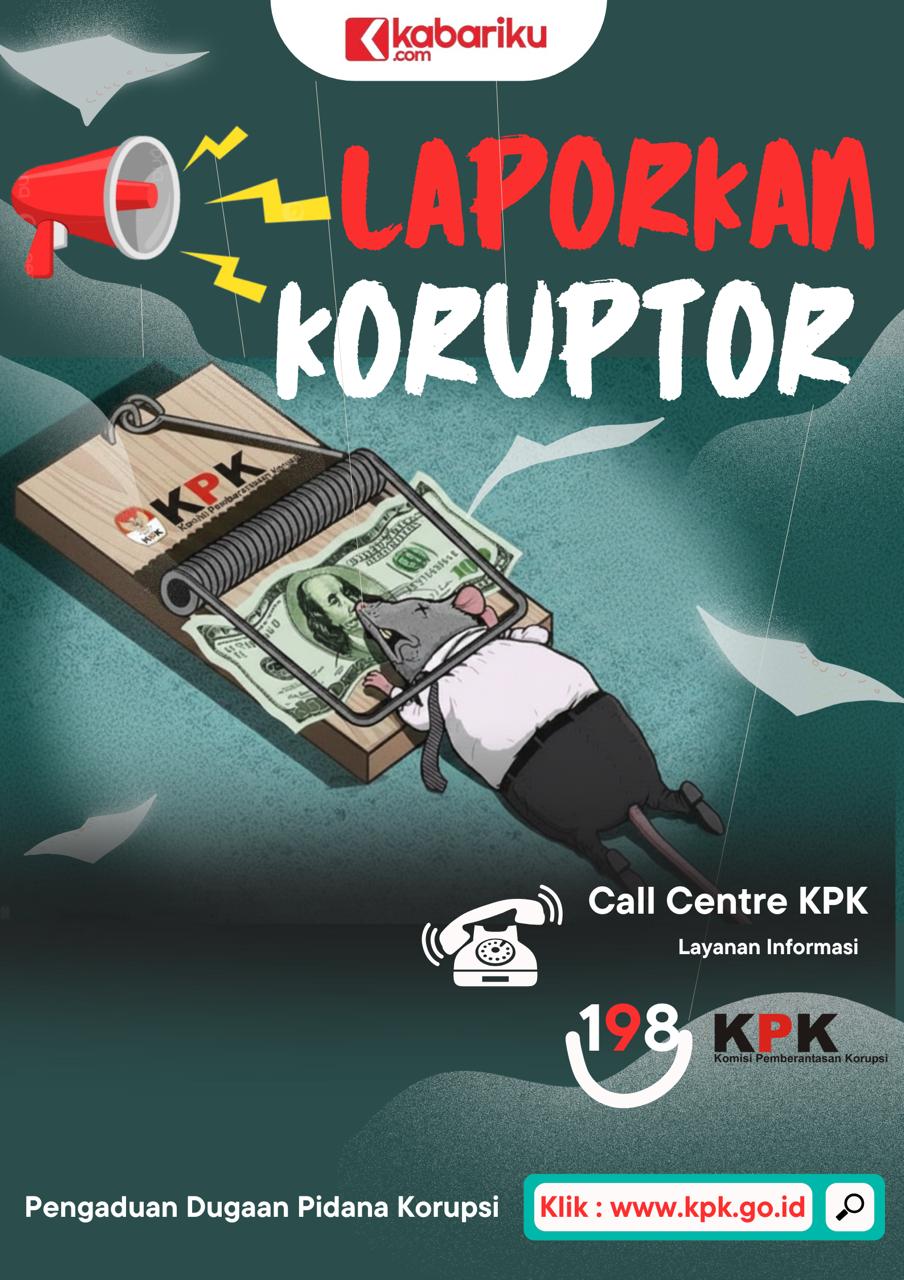
















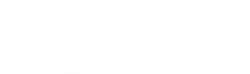
Discussion about this post