Oleh Marlin Dinamikanto (Penulis, aktivis)
KABARIKU – Naik-naik semua harga, tinggi-tinggi sekali
Naik-naik semua harga, tinggi-tinggi sekali
Kiri-kanan kulihat saja, rakyat hidup sengsara
Kiri-kanan kulihat saja, rakyat hidup sengsara
Plesetan lagu “Naik-naik ke Puncak Gunung” itu dinyanyikan di sepanjang jalan, sejak pertigaan Taman Safari, Puncak, hingga masuk tol Cawang Jakarta. Sore itu, sekitar bulan September 1997, kami pulang dari pelatihan LAR (Latihan Aksi Reformasi) Pijar Indonesia. Kebanyakan peserta LAR, anak-anak muda Palembang yang baru saja membuat cabang Pijar di kotanya. Saya satu mobil dengan anak-anak Palembang yang sebagian berlatar-belakang aktifis pecinta alam Komunitas (K) 9, seniman, pemuda dan mahasiswa.
Memang, sejak Juli 1997 itu tercatat semua harga kebutuhan pokok naik. Harga nasi telor di warteg yang sebelumnya Rp.700 mendadak naik menjadi Rp.2500. “Ya, istilahnya jual untung beli rugi,” ucap pemilik warung langganan ngutang anak-anak Pijar, di Jl Pedati, Kampung Melayu. Bayangkan saja, harga terus berubah. Sebut saja harga gula, dari sekarung Rp.20 ribu dijual Rp.22 ribu besoknya ke grosir harga sudah Rp.23 ribu. Pemilik warung rumahan pun satu per satu item dagangannya menyusut. “Bulan lalu belanja Rp 100 ribu sudah komplit, sekarang Rp 200 ribu nggak ada separohnya,” ungkap seorang pemilik warung rumahan dekat kantor Pijar, sekitar awal Agustus 1997.
Perubahan harga yang drastis itu sungguh saya rasakan. Sebelumnya saat kantor Pijar di Percetakan Negara, antara Juli 1996 – Juni 1997, dengan uang Rp 10 ribu saya yang menjabat pimpinan redaksi Kabar dari Pijar, bisa mentraktir sekaligus 10 orang, tapi sejak pindah di sebuah gang di Jalan Pedati, Kampung Melayu, kalau hanya punya duit sebesar itu terpaksa makannya ngumpet-ngumpet. Kalau tidak begitu terpaksa harus ngutang. Pertama, harga makanan sudah naik 4 kali lipat, dan kedua anggota Pijar, seiring dengan berdirinya Forum Kesenian Reformatif (Foker), underbouw Pijar yang beranggotakan pengamen jalanan, sehari-harinya yang di kantor sudah lebih dari 10 orang. Singkat cerita, kondisinya saat itu betul-betul sulit.
Krismon dan Foker
Orang-orang saat itu menandai kondisi melambungnya harga-harga kebutuhan pokok dengan sebutan Krismon, alias krisis moneter. Sejak pertengahan Juli 1997 hingga pamitnya Soeharto dari singgasana kekuasaan pada 21 Mei 1998, situasi ekonomi memang tidak menguntungkan siapapun yang berkuasa. Nilai rupiah terhadap dolar AS, anjlok dan mencapai puncaknya pada 8 Januari 1998. Saya ingat, karena 7 Januari ulang tahun saya yang diperingati kawan-kawan aktivis di Palembang, nilai per 1 dolar AS mencapai Rp 14 ribuan. Sejak itu kehidupan kaum miskin di perkotaan ibarat ilalang kering, mudah sekali terbakar. Tidak terkecuali hidup para pengamen jalanan yang kami himpun dalam Foker.
Meskipun begitu, anak-anak Foker yang kami rekrut sejak Pijar berkantor di gang samping pesantren Assyiifiyah, Jl Barkah, Manggarai, awal 1996 itu bisa menghidupi dirinya dengan mengamen. Acap kali pula mereka patungan untuk membayari saya dan anak-anak Pijar lainnya saat makan di Warteg. Adakalanya pula, misal saat seorang aktivis yang menginap di Pijar, saya lupa namanya, mau pulang ke Makassar, serentak anak-anak Foker patungan dan terkumpul Rp.230 ribu yang selanjutnya diberikan ke kawan aktivis itu pulang ke Makassar lewat Surabaya. “Ya, paling tidak sampai Surabaya,” ucap Almarhum Ocup Akar, pengamen jalanan asal Palembang yang biasa ngamen di Terminal Pasar Senen.
Dengan adanya Foker, selain tetap menulis Kabar dari Pijar, saya yang pernah sekolah jurusan musik di IKIP Jakarta bisa menyalurkan bakat musik. Setiap malam, terutama saat kantor Pijar di Jalan Percetakan Negara, saya, (alm) Ucup Akar, Eko Biola, Pak Tua, dengan bintang tamu Taufiq Wijaya, penyair asal Palembang, berlatih musik. Pernah pentas dalam acara Ulang Tahun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 28 Oktober 1996, sudah itu kami juga pentas musik di kantor Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Jakarta Pusat. Saat itu kami dibiayai Walhi dan Infid untuk menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di semenanjung Muria, Jawa Tengah.
Dalam latihan, saya menyuplai lagu-lagu plesetan ke para seniman jalanan. Selain itu saya juga berkreasi dengan lagu-lagu sendiri. Paling tidak, dengan kegiatan berkesenian, saya ingin spirit perlawanan untuk perubahan iklim politik yang lebih baik terus menyebar lewat seniman jalanan di bus-bus kota, di kereta api Jabotabek, di terminal, di trotoar warung-warung tenda. Ternyata tanggapan masyarakat oke. Terbukti, setiap menyanyikan lagu-lagu kritik sosial, ada kalanya penumpang bus kota memberikan duit ribuan, lima ratusan, bukan lagi uang merah seratusan rupiah seperti Pak Ogah. Jadilah para seniman jalanan, dengan kreasi masing-masing, bahkan ada yang hanya membaca puisi atau mendongeng, berlomba-lomba melakukan kritik kepada pemerintah yang tampak begitu digdaya menculik dan menangkapi mahasiswa.
Pengamen jalanan yang semula hafal luar kepala lagu-lagu nostalgia, satu per satu beralih ke lagu-lagu kritik sosial, karena memang lebih mampu mencuri perhatian penumpang bus kota, kereta api atau penjaja warung di terminal dan trotoar. Ada diantara mereka sudah bergabung menjadi aktivis Jaringan Kesenian Rakyat (Jaker) yang dibentuk PRD, tapi tidak sedikit pula yang ikut Foker. Anggota Foker yang saat Pijar berkantor di Percetakan Negara hanya paling banyak sepuluh orang, saat berkantor di Pedati anggotanya ratusan orang. Setiap hari mereka berlatih, ada pula yang mencoba jadi penyair, membuat suasana kantor Pijar berisik. Pagi hingga sore hari mereka menyebar ke seluruh penjuru Jakarta. Ngamen.
Sering kali pula saya ikut-ikutan ngamen. Diantara lagu-lagu plesetan yang saya buat, paling ngetop Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki yang saya plesetkan menjadi Indonesia Tanah Air Siapa, hingga lagu plesetan itu dinyanyikan anak-anak mahasiswa hampir di semua kota besar Indonesia. Cerita itu rupanya bermula saat saya sering memberi materi Manajemen Aksi dalam Latihan Kaderisasi (LK) HMI yang kadang pesertanya dari berbagai perguruan tinggi Indonesia. Mungkin lewat kader-kader HMI yang juga pernah saya ikuti, bahkan saya pernah didaulat menjadi Ketua Umum Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Cabang Jakarta, lagu “Indonesia Tanah Air Siapa” yang liriknya saya tulis di rumah Bang Bursah Zarnubi itu, menjadi semacam lagu wajib demo-demo mahasiswa kala itu.
Indonesia, tanah air siapa
Katanya tanah air beta,
Indonesia sejak empat lima
Janjinya rakyat sejahtera
Nyatanya kini kubertanya
Petani digusur sawahnya
Buruh murah miskin dan sengsara
Sampai akhir menutup mata.
Prasangka Anti China
Membubungnya harga-harga kebutuhan pokok itu, acap kali diikuti oleh aksi penimbunan. Pelakunya memang bisa siapa saja. Tapi anggapan umum mengatakan, mungkin karena kebanyakan grosir dimiliki warga keturunan China, maka tidak sedikit diantara warga pribumi menduga, aksi penimbunan barang yang dianggap sebagai biang keladi naiknya harga-harga kebutuhan pokok itu dilakukan orang China. Tidak aneh bila setahun kemudian, tepatnya sejak 13 Mei 1998, orang-orang ini dengan mudah terprovokasi untuk menjarah toko-toko warga keturunan China.
Saya sering bergaul di warung-warung kopi dan pos ronda. Dalam perbincangan kadang ada-ada saja terselip ucapan rasialis anti-China. “Dulu jaman Bung Karno mereka hanya boleh tinggal di Kota Kabupaten, sekarang ada dimana-mana,” begitu ucapan yang sering saya dengar. Ada pula yang menimpali, kita disuruh-suruh KB, kalau mereka dibiarkan beranak banyak. Lama-lama kita dikuasai mereka. Satunya lagi ngomong, mereka pelit, sama diri sendiri saja pelit, kalau belum kaya makannya cuma pakai kecap. Tidak satu pun yang mengulas, betapa Susi Susanti dan suaminya Alan Budi Kusuma, pahlawan Olimpiade, termasuk juga Ruddy Hartono, Liem Swee King dan Lius Pongoh berdarah keturunan China.
Sudah sejak kecil saya menolak anggapan itu. (Alm) Sudiyono, bapak saya, selalu menekankan, orang bisa jadi China, jadi Jawa, jadi Batak, itu bukan kehendak yang bersangkutan, tapi sudah takdir yang Maha Kuasa. “Jadi jangan sekali-kali benci sama orang karena latar belakang ras, keturunan atau agamanya,” begitu ucapnya yang saya dengar sejak saya kecil. Di keluarga pun, bapak yang muslim membebaskan istrinya memeluk agama yang berbeda. Ibu kandung saya memeluk agama Katholik Roma, ibu tiri saya yang mengasuh saya sejak kecil beragama Kristen Protestan, malah aktif di Gereja Kristen Jawa Nehemia, Lebakbulus, Jakarta Selatan. Begitu juga adik-adik saya, agamanya ada yang Islam, ada yang Katholik Roma dan ada pula yang Kristen Protestan, toh kami tidak pernah meributkan soal agama.
Dalam kehidupan sehari-hari pun, saya bergaul dengan Batak, Padang, Betawi, Arek, Ambon, Bugis, Kristen, Sikh, Hindu, Budha, Atheis, Komunis, PSI, Masyumi, Syiah, Wahabi, Ahmadiyah, NU, Muhammadiyah, siapa saja. Bahkan karena luasnya pergaulan itu membuat saya dicap nggak jelas. Oleh orang HMI dicap kader semangka, oleh yang non HMI dibilang mata-mata, tapi saya tetap berpegang teguh dengan prinsip multi-kulturalisme yang diajarkan Bapak saya. Toh saya sulit menjelaskan dengan bahasa gamblang tentang pendapat umum yang secara tidak adil menyudutkan keberadaan suatu rasa atau golongan. “Mereka terlahir jadi China itu bukan kehendaknya, tapi kehendak Yang Di Atas. Berarti pula kalau membenci China berarti membenci kehendak Tuhan,” ucap saya memberi silogisme sederhana, tapi toh tetap saja hanya sedikit diantara orang yang saya ajak bicara percaya omongan saya.
Berkali-kali pula saya beri contoh, kalau di belakang pertokoan Glodok, di Tangerang, di Palembang, di Kalimantan Barat, tidak sedikit pula orang China yang lebih miskin dari kita. Jadi tidak semua seperti Edy Tansil yang menggarong uang Negara Rp 1,3 triliun. Kalau ada yang ulet, gesit berusaha dan akhirnya berhasil memang itu bidang dia. “Mestinya pejabat yang gajinya tidak seberapa tapi hidup kaya raya yang perlu dicurigai.” Tetap saja penjelasan saya dianggap angin lalu. Anggapan umum tetap mengatakan kalau China itu biangnya penyogokan, penyelundupan, penimbunan, sehingga mereka menguasai mata-rantai ekonomi nasional.
Anggapan itu semakin subur seiring badai Krismon yang membuat terjadinya PHK besar-besaran. Apa lagi bila perusahaan yang melakukan PHK itu, bos-bosnya, sejak pemilik hingga manajer di tingkat bawah dikuasai orang-orang bermata sipit. “Kalau untung dimakan sendirian, kalau rugi kita dijadikan korban,” ucap seorang penggiat aktivis buruh bernada rasis. Padahal, berapa bos, misal saja warteg yang pribumi menggaji karyawannya, sudah pasti kebanyakan seadanya, meskipun ada diantara mereka yang baik hati memberi insentif karyawannya, tapi kebanyakan (seperti umumnya para bos) terus membuka cabang usahanya dan hidup kaya raya di kampungnya. Tapi pandangan saya ini pun tetap tidak mempan mematahkan anggapan umum tentang keturunan China yang konon sudah dibentuk sejak jaman kolonial.
Pandangan anti-China ini, meski tidak eksplisit, acap kali pula mencuat dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan Center Indonesia for Development and Studies (Cides), lembaga ting teng bentukan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang konon untuk mengimbangi kiprah Center for Strategic of International Studies (CSIS), lembaga ting teng bentukan Ali Murtopo yang dalam pandangan mereka dikendalikan oleh kelompok Benny Murdani. Sulit dipungkiri pula, perpecahan di tubuh elite Orde Baru, baik yang di CSIS, ICMI atau kelompok lainnya, diam-diam membuat perpecahan elite jalan mengendap-endap, sedangkan di permukaan situasinya, mengutip bahasa intel, tampak aman terkendali.
Pengendalian situasi dengan cara represif, tampak terlihat paska penyerbuan 27 Juli. Sejak itu kasus penangkapan aktivis berjalan massif. Beberapa diantara aktivis yang menjadi target operasi sembunyi di gereja. Tapi toh keberadaan mereka tercium intel. Saat lengah, atau lupa pulang ke rumah seperti Garda Sembiring, mereka ditangkap. Dalam pidato tahun baru 1997, Presiden Soeharto secara khusus menyinggung kebijakan represif yang dilakukan anak buahnya. “Gejolak-gejolak tadi ada yang dilatarbelakangi oleh sebab-sebab sosial, budaya, politik, ekonomi maupun agama. Kita bersyukur bahwa gejolak-gejolak itu dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya,” begitu ucap Pak Harto sebagaimana saya kutip dari website pribadi A. Umar Said.
Konsolidasi Gerakan
Dengan kata lain, kami aktivis gerakan yang tidak terkait dengan lembaga-lembaga bentukan Orde Baru itu, terhitung sejak kantor PDI di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri pada 27 Juli 1996 diserbu preman (ada pula anggapan sebagian diantara penyerbu aparat militer) berkaos PDI Pro Suryadi, betul-betul tiarap. Kami aktivis gerakan yang oleh Anders Uhlin disebut Oposisi Berserak semula bergabung ke sejumlah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dan organisasi-organisasi perlawanan seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Pijar, lembaga-lembaga bantuan hukum, lembaga-lembaga lingkungan hidup, lembaga-lembaga HAM, organ-organ gerakan mahasiswa di kota-kota besar, sempat shock seiring pengejaran dan penangkapan besar-besaran aktifis PRD dan jaringannya. Budiman Sudjatmiko yang secara pribadi saya kenal karena sering minta rokok Marlboro di kantor YLBHI, ditangkap. Begitu juga dengan Dita yang saat kantornya kebanjiran mengungsi ke kantor Pijar di Barkah, Manggarai, sudah ditangkap lebih dulu saat demo buruh di Sidoarjo, Jawa Timur. Pun Garda Sembiring dan Iwan yang masih ponakannya Romo Bambang, kawan saya di Palembang juga diciduk, termasuk Wignyo pacarnya Dita, Petrus dan aktivis lainnya yang saya lupa namanya.
Saya dan teman-teman Pijar pun, meski berkali-kali berusaha melawan dengan melakukan aksi kecil-kecilan, seperti misal pengembalian kartu kuning, kartu undangan mencoblos, ke Komnas HAM menjelang Pemilu 1997, toh tetap saja merasakan ruang gerak tidak seleluasa hari-hari sebelum meletusnya peristiwa 27 Juli. Persidangan Sri Bintang pun kami jadikan semacam ajang silaturahim bagi aktivis yang ibarat burung kehilangan bulu. Itu pun situasinya tidak segempar saat persidangan Nuku Soleman, persidangan Tri Agus Siswowihardjo yang menjabat pimpinan redaksi Kabar dari Pijar sebelum saya, atau persidangan 21 mahasiswa aktifis Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) yang ditangkap pada 14 Desember 1993 di kantor DPR karena membuat spanduk, Tangkap dan Adili Presiden Soeharto ke Sidang Istimewa MPR.
Saat itu pula ada persidangan kelompok 124. Ke-124 orang itu kader dan simpatisan PDI Pro Mega yang ditangkap di kantor PDI saat penyerbuan. Saya sering datang ke persidangan itu sekaligus mencatatnya. Tidak lupa pula, atas perintah Trimedya Panjaitan dan Amien Aryoso, saya kliping berita persidangan itu secara lengkap. Nah dari berkas-berkas tuntutan, berkas-berkas pleidoi, catatan persidangan dan kliping-kliping itu saya sunting menjadi buku berjudul Perjuangan Merebut Benteng Keadilan. Judul buku itu diusulkan oleh (Alm) RO Tambunan yang kemudian bersama Megawati Soekarnoputri menulis kata pengantar. Buku itu juga dilengkapi hasil investigasi kawan wartawan yang menyembunyikan identitasnya sehingga kami tahu, para penyerbu itu berasal dari Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur dan Kapuk, Jakarta Barat, yang sebelum menyerbu diinapkan di parkiran belakang Polda.
Memang, usai penyerbuan 27 Juli, ratusan lawyer yang digalang RO Tambunan, (Alm) Amartiwi Saleh, Amien Aryoso, Trimedya Panjaitan, Dwi Ria Latifa, Petrus Bala Patyona itu sepakat membentuk Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Tugasnya selain mendampingi Kelompok 124 juga melakukan gugatan hukum atas diselenggarakannya Kongres Medan. Ternyata pula, TPDI juga muncul di hampir semua ibu kota Kabupaten se-tanah air, dengan melibatkan ribuan pengacara. Gejala itu disebut majalah Time sebagai gerilya hukum. Sejak itu pula muncul Posko-Posko Gotong Royong di sepenjuru Nusantara. PDI Pro Mega yang menjelang Pemilu 1999 berganti nama PDI Perjuangan itu mengkonsolidasikan kekuatannya tanpa ingar binger protes, cukup dengan main gaple dan wedangan di Posko bercat merah bergambar Megawati.
Paska penyerbuan 27 Juli, kantor YLBHI tampak dari luar sepi, tapi di dalamnya puluhan aktivis tampak berkumpul. Halaman YLBHI tidak semeriah sebelumnya. Karena itu pula, di pagar-pagar luar kantor YLBHI bermunculan para pedagang kaki lima. Ada tukang Soto, ada tukang gado-gado, penjual gorengan dan lainnya. Maklum di tahun-tahun Oposisi Berserak itu YLBHI menjadi semacam kantor bersama para aktivis dari berbagai organisasi. Seingat saya, PRD, Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dideklarasikan di kantor yang didirikan Adnan Buyung Nasution pada tahun 1970-an itu. Ketiga organisasi itu, seingat saya pula didirikan antara 1995 – 1996. YLBHI memang terbuka bagi siapa saja untuk rapat, bahkan rapat aksi sekalipun. Tidak mengherankan bila intel, dengan berbagai kedok, turut berkeliaran di sana.
Di YLBHI pun saya ingat, bagaimana rapat pertama saat pembentukan KIPP, sekitar awal tahun 1996. Di sana ada Kastorius Sinaga, Mulyana W Kusumah, dan sejumlah aktivis dari PMII dan PMKRI. Seingat saya Gunawan Muhamad belum hadir saat rapat pembentukan. Saya mewakili Pijar, namun saat pembentukan Presidium saya mengusulkan Beathor Suryadi yang baru keluar dari penjara sebagai Presidium yang mewakili Pijar. Maka diantara anggota Presidium KIPP yang dideklarasikan 17 Maret 1996, tercatat Beathor sebagai anggota Presidium. Ketua Dewan Presidium Gunawan Muhamad, Sekretaris Jenderal Mulyana W. Kusumah, anggota-anggotanya, selain Beathor ada Chatibul Umam Wiranu, Muhamad Nadjib Sinulingga, Standarkiaa, Budiman Sudjatmiko, Saut Sirait, (Alm) Tohap Simanungkalit, FX Dodi Geger dan Andi Arief. Sedangkan Dewan Penasehatnya ada 35 orang, diantaranya Adnan Buyung Nasution, (Alm) Nurcholis Madjid, Pendeta SAE Nababan, (Alm) Dahlan Ranuwihardjo, Zumrotin dan lain-lain.
Satu hal yang perlu dicatat, KIPP bisa terbentuk dengan melibatkan beragam tokoh dan kaum cerdik pandai dari berbagai latar belakang, tidak terlepas dari kegigihan Nia Sjarifuddin dalam menghubungi para tokoh. Saya tahu persis itu, karena saya ikut sejak proses pembentukannya di kantor YLBHI dan berlanjut ke pertemuan di Puncak yang dibubarkan intel. Tanpa kegigihan Nia yang saya kenal sejak dia mengurus Masyarakat Anti Nuklir Indonesia (MANI) dalam memburu dan meyakinkan tokoh, baik lewat telepon atau kunjungan langsung ke rumah, maka KIPP mungkin hanya beranggotakan orang yang itu-itu saja, dan dengan begitu tidak terlalu dianggap oleh penguasa. Namun keberhasilan Nia meyakinkan Nurcholis Madjid dan sejumlah tokoh yang sebelumnya tidak beredar di lingkungan aktifis gerakan, maka penguasa di berbagai level pun gerah atas kehadiran KIPP.
Sejak dideklarasikan hingga 31 Mei 1996, surat kabar nasional diisi berita-berita yang menolak KIPP karena dianggap ilegal. Bahkan di Jawa Timur, Gubernur Basofi Sudirman menyiapkan PIKIPP untuk memantau KIPP. Di Jakarta, lewat Center for Policy and Development Studies (CPDS), sebuah organisasi riset non-konvensional yang punya hubungan spesial dengan kalangan tertentu di tubuh militer dan birokrasi, keberadaan KIPP terus digoyang dengan berbagai argumentasi dangkal. Dalam publikasi [email protected], milling-list yang diasuh John MacDougall, dalam artkelnya berjudul CPDS, Cendana dan Markas Intel, disebutkan, KIPP yang dipimpin Gunawan Muhamad terbentuk karena TEMPO dibredel. Kredibilitas pengurus KIPP, terutama yang berasal dari YLBHI disebut-sebut sebagai barisan sakit hati. Mereka juga menuduh KIPP ditunggangi kelompok Katholik yang dikendalikan Benny Murdani. Sedangkan kehadiran tokoh ICMI Nurcholis Madjid karena dipolitisir. Proses delegitimasi KIPP pun dilakukan secara massif oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Affan Ghafar, Amir Santoso, Fadli Zon dan lainnya yang bergabung dalam kelompok Jalan Suwiryo.
Pernah suatu saat, di kantor KIPP di perkampungan padat penduduk kawasan Dewi Sartika, setiap Mas Mul, begitu kami biasa memanggil Mulyana W Kusumah, masuk kantor, segera saja intel yang sembunyi di warung depan kantor KIPP dengan handy talkynya berkata, “Kancil gondrong masuk sarang.” Saya yang aktif di KIPP selama masa perjuangan itu, artinya sebelum KIPP digelontor dana UNDP Rp 21 miliar dan juga sebelum berkantor di Rawamangun, merasakan betul betapa mencekamnya tinggal di kantor KIPP. Pernah, suatu saat usai pencoblosan Pemilu 1997 saya tidur sendirian di kantor. Rupanya, malam itu muncul desas-desus kantor KIPP mau dibom, sehingga pekerja-pekerja KIPP diungsikan ke sebuah hotel di Jl Raden Saleh. Maka pagi harinya, saat wartawan asing berkumpul, saya pun menjadi narasumber, dan saya tidak tahu apakah wawancara itu dimuat atau tidak. Karena secara resmi saya tidak tercatat sebagai apa-apa di KIPP, selain sebagai aktivis yang berkumpul di sana.
Dua isu utama menjelang Mei 1998 adalah demokratisasi dan Hak Azasi Manusia. Lingkungan Hidup memang ada tapi tidak terlalu menonjol. Bahkan Walhi, Ornop Lingkungan yang menonjol saat itu tampak terlibat aktif dalam advokasi penggusuran seperti yang pernah saya lakukan di Sumsel antara Desember 1994 hingga Agustus 1995. Pernah, pas meletus peristiwa 27 Juli, saya numpang rombongan bus petani korban penggusuran Sumsel yang difasilitasi Walhi. Bus mengangkut rombongan dari LBH Palembang. Saya sudah mendengar, di Jakarta kantor PDI diserbu. Dalam situasi was-was itu bus tetap berangkat. Sampai Jakarta, Minggu 28 Juli, jalanan tampak sepi. Tampak sebuah helicopter meraung-raung di udara. Kalau tidak salah, bus langsung mendrop petani di kediaman (Alm) Munir, di Jatinegara, tepatnya belakang kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Ternyata, kantor Pijar di hari yang lengang itu sudah pindah dari Barkah ke Percetakan Negara. Ya, Pijar memang setiap tahun kantornya dipaksa pindah. Pemilik rumahnya selalu ditakut-takuti intel.
Selain KIPP, di YLBHI itu pula, awal 1997 berdiri Komite Independen Pemantau Pelaksanaan Hak Azasi Manusia (KIPP-HAM) yang dideklarasikan oleh 5 organisasi non pemerintah (Ornop). Juni – Oktober 1997, KIPP-HAM menggelorakan isu perlunya TAP MPR yang mengatur tentang hak azasi manusia sebagai bentuk pengakuan Negara atas piagam semesta HAM. Apalagi sepanjang 1997, seiring mencuatnya tindakan represif paska 27 Juli 1996 berlanjut ke krismon, tercatat 1600 masyarakat sipil menjadi korban penangkapan dan penganiayaan. Tapi upaya KIPP-HAM tidak begitu dianggap pemerintah. Tindakan represif terus dilakukan.
Puncaknya, menjelang Sidang Umum MPR 1-11 Maret 1998, tepatnya Februari 1998 mulai terjadi penculikan aktivis. Para aktivis pun diam-diam berkumpul di YLBHI, membahas kasus-kasus penculikan yang menimpa rekan-rekannya. Tapi apa yang terjadi, 12 Maret 1998, paska terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden, tiga orang aktifis masing-masing bernama Herman Hendrawan, hingga kini tidak jelas keberadaannya, Faisol Reza dan Raharjo Waluyo Jati yang akhirnya dipulangkan oleh para penculiknya, tiba-tiba raib sepulangnya dari kantor YLBHI. KIPP-HAM mulai melacak keberadaan mereka, menemui keluarga para korban. Dari pertemuan dengan keluarga korban itu tercetus gagasan membuat lembaga yang lebih spesifik mengurus orang hilang dan korban tindak kekerasan. Sejak itu pula, tepatnya pada 20 Maret 1998, berdirilah Komite Orang Hilang dan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat KontraS. Tercatat 12 organisasi sebagai pendiri, antara lain YLBHI yang dipimpin Bambang Wijayanto, Elsam yang dipimpin Abdul Hakim Garuda Nusantara, Lapasip yang dipimpin Agus Edy Santoso, termasuk dua organisasi mahasiswa ekstra-kurikuler, PMII dan GMNI.
“Tadinya, KontraS itu Komite Korban tindak kekerasan Soeharto, maka huruf S di paling belakang itu huruf besar (capital),” ungkap Standar Kiaa, aktivis Universitas Nasional yang juga tercatat sebagai pendiri KontraS. Kalau tidak salah, awal dibentuknya KontraS, (Alm) Munir diangkat sebagai Direktur Eksekutif. Di situlah keberanian Munir dibuktikan. Bukan para aktifis saja yang berusaha diselamatkannya, melainkan juga “aktifis” Pam Swakarsa yang dikepung massa saat tahlilan di Tugu Proklamasi. Massa yang datang dari perkampungan sekitar Tugu Proklamasi marah, karena diantara peserta tahlilan itu didesas-desuskan tercium bau alcohol. Di samping itu mereka dicap sebagai antek penguasa. Oleh Munir para peserta tahlilan itu dievakuasi keluar dari areal Tugu Proklamasi.
Tanda-Tanda Jaman
Bila di perkotaan aktivisnya sibuk berkonsolidasi dalam beragam gerakan, termasuk mimbar bebas hampir di semua kampus perguruan tinggi, swasta maupun negeri, sedangkan penduduk miskin sudah pasti bertambah seiring melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, di desa-desa, khususnya daerah penghasil pangan kondisinya hampir serupa. Sepanjang musim krismon itu iklim ikut-ikutan tidak bersahabat. Kemarau datang begitu panjang alias Elnino. Pohon karet dan rambutan mengering. Sawah kerontang. Ladang gersang berdebu. Tidak mengherankan di Gunungkidul, kampung halaman saya, warga menjual murah sapinya yang kurus kering, karena kalau tidak dijual pasti mati. Itu saya lihat sendiri saat pulang kampung sekitar awal 1997.
Seorang paranormal, kebetulan masih kerabat besar saya, menyarankan agar tetangganya yang merantau di Jakarta lekas pulang. “Jakarta banjir getih (darah),” ucapnya sebagaimana yang saya dengar. Ucapan itu dia ungkap sejak 1996 setelah kantor PDI diserbu preman. Beberapa saudara terpengaruh dengan ucapan paranormal yang masih terhitung paman saya itu. Ada yang sebelumnya jadi bidan sukses di Karawang menjual assetnya dan pulang ke Gunungkidul, ada pula yang di Cilegon dan Jakarta. Malah ada yang sampai sekarang menetap di sana, wira usaha kecil-kecilan dengan membuka dealer motor China. Hanya saya dan keluarga saya yang tetap di Jakarta. “Mati urip ki tergantung sing Maha Kuasa,” ucap (Alm) Soediyono, ayah saya tanpa bermaksud mengabaikan peringatan paman saya yang paranormal top di kampungnya.
Di Lampung pun kondisinya tak jauh berbeda. Saat bertandang ke rumah Pak De saya di Proyek Pemukiman Angkatan Laut (Prokimal), Kota Bumi, Lampung Utara, sekitar 1997 juga, kehidupan petani betul-betul mengenaskan. Harga lada, kopi, memang membubung tinggi. Tapi banyak pohon yang mati akibat kekeringan. Kopi memang sedikit bertahan, tapi buahnya kalau biasa panen 3 kuintal paling panen tidak sampai 1 kuintal. Toh begitu tingginya harga kopi yang biasanya hanya laku Rp 3 ribu per Kg kini membubung menjadi Rp 15 ribu menjadi katup penyelamat, khususnya bagi warga yang masih memiliki kebun kopi. Sebab tidak jarang, saat harga kopi bertahun-tahun anjlok, tidak sedikit pohon kopi yang ditebangi dan diganti dengan tanaman singkong atau lada. Nah, petani yang telanjur mengganti kebun kopinya dengan tanaman singkong ini yang biasanya jadi korban.
Perlu diakui pula, tidak semua petani dirugikan Krismon. Pertengahan 1997 pernah saya dan teman-teman seniman Palembang diundang Syamsu Indra Usman, seorang pesirah di Lubuk Puding, Kabupaten Empatlawang (dulu masih bagian dari Lahat). Pesirah yang maaf kata, bertubuh bungkuk itu juga dikenal sebagai seniman di daerahnya. Mengajar Teater di SMP Ulumusi. Karena panen kopinya melimpah, mereka mengundang kami, antara lain Vebri Al Litani yang kemudian menjadi ipar saya, Filus Mursalin yang seniman musik, Anwar Putra Bayu yang penyair dan selebihnya saya lupa. Ternyata, kehidupan petani ikopi di Semendo, Muaraenim dan Pagaralam yang kami lalui mendadak makmur. Mobil-mobil bekas bersliweran di jalanan desa yang kering berdebu. “Jajan anaknya saja pake duit lima puluh ribuan,” ucap Kak Vebri yang kini aktif di Dewan Kesenian Sumatera Selatan.
Di Bangka yang penghasil lada dan Sulawesi Selatan penghasil coklat kabarnya juga makmur oleh anjloknya nilai rupiah. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, seperti YLBHI dan Elsam yang mendapat sumber pendanaan berupa gulden atau dolar AS, bisa jadi diuntungkan oleh kondisi itu. Terbukti YLBHI bisa merenovasi kantornya, sedangkan Elsam bahkan mampu membeli kantor di Pasarminggu, dari sebelumnya berkantor di dekat terminal Kampung Melayu yang rawan banjir. Perseorangan yang menyimpan dolar pun beruntung. Ibu teman saya, aktivis LSM di Palembang, bisa membeli mobil Kijang akibat melonjaknya nilai dolar. Harga mobil Kijang masih Rp 35 juta, maka saat dolar melejit mereka pun buru-buru menukarkannya dan membeli mobil yang harganya terhitung murah.
Tapi kehidupan rata-rata warga miskin di kota-kota besar, termasuk Jakarta dan Palembang, dua kota yang berganti-ganti saya diami, umumnya mengenaskan. Sumber penghidupan, seiring terjadinya PHK massal di pabrik-pabrik, semakin sulit dicari. Maka uang pesangon pun digunakan membuka usaha, ada yang bertarung dengan tetangga membuka warung rumahan, ada pula yang nekad menjadi pedagang kaki lima. Saat itu, Jakarta maupun Palembang, terlihat semrawut. Masing-masing penguasa kota, Gubernur Suryadi Sudirdja di Jakarta dan Walikota Palembang Husni sulit bertindak tegas, karena itu menyangkut urusan perut. Mungkin bila saat itu ditertibkan, suasananya lebih dulu bergolak sebelum Mei 1998.
Orang-orang desa di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera yang menjadi korban kekeringan, berlomba-lomba eksodus ke kota terdekat. Setidaknya di kota, bila ada kemauan pasti sekedar makan pun bisa. Maka, selain pedagang kaki lima, gelandangan, pengemis, pengamen, menjadi pemandangan umum di pusat-pusat keramaian Jakarta dan Palembang. Pemerintah tampak lebih sibuk mengendalikan stabilitas politik dengan menindas para aktivis, sedangkan di tubuh pemerintah sendiri diindikasikan terbelah. Kala itu muncul rumor, terjadi persaingan antara tentara hijau, antara lain Feisal Tanjung dan Hartono, melawan tentara merah putih yang antara lain dengan tokoh Eddy Sudrajat dan Agum Gumelar. Belum lagi persaingan antara Wiranto dan Prabowo. Menteri-menteri pun tampak tidak solid, misal dalam menanggapi Pernyataan Komnas HAM tentang indikasi pelanggaran HAM berat dalam kasus 27 Juli, ada beda pendapat antara Mendagri Syarwan Hamid dan Menteri Komunikasi, Telekomunikasi dan Pariwisata (Alm) Susilo Sudarman. Yang satu keras dan yang satu lunak.
Mahasiswa Bergolak
Situasi yang serba tidak pasti itu terus mengayun. Masyarakat pada umumnya, termasuk kelas menengah terdidik seperti mahasiswa, merasa tidak pasti dengan masa depannya. Pegawai pemerintahan merasa tidak pasti dengan keberlangsungan jabatan sang big bos Soeharto. Begitu juga dengan tentara-tentara yang di permukaan tampak represif memburu aktivis tapi di belakang, para perwiranya sibuk menyiapkan sekoci bila terjadi apa-apa dengan pemerintahan Soeharto, ada yang ke Megawati seperti Agum Gumelar, ada yang ke Amien Rais, ada pula yang merapat ke Gus Dur. Ilalang kering itu tidak hanya meranggas kaum miskin kota melainkan juga menjangkit ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk birokrat sipil dan militer yang telah mencium tanda-tanda tumbangnya Soeharto.
Setelah Sidang Umum MPR 1998, seingat saya sejak April 1998, sejumlah kampus perguruan tinggi di Jakarta dan beberapa kota besar, termasuk Palembang, sudah mulai melakukan mimbar bebas di kampus masing-masing, secara simultan dan bergantian. Pengurus Senat Mahasiswa di masing-masing Fakultas pun mulai melibatkan diri dalam mimbar bebas, dengan tuntutan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Muncul pula spanduk turunkan harga yang secara eksplisit dipanjangkan menjadi Harto dan Keluarga. Kampus-kampus yang tidak melakukan mimbar bebas dikirimi celana dalam perempuan, bias gender memang, tapi itu sebagai sindiran supaya mahasiswa dibangkitkan keberaniannya.
Pusat gerakan pun menyebar. Kalau sebelumnya hanya di seputaran Diponegoro, antara kantor YLBHI dan kantor DPP PDI, kini menyebar ke hampir semua kampus perguruan tinggi, negeri atau swasta, termasuk kampus-kampus yang selama ini menjadi tempat favoritnya kuliah mahasiswa-mahasiswa keturunan China, seperti Tri Sakti, Tarumanegara, Atmadjaya, Bina Nusantara dan lainnya. Artinya, semua anak bangsa, pribumi maupun China, sama-sama menginginkan perubahan di negeri tercinta. Bahkan saya mencatat, sejak Soehato masih kuat-kuatnya, kami sering bertemu mahasiswa keturunan China setiap aksi, misal Sisi dari Bogor dan Wiwil Salatiga yang jadi pemicu konflik asmara di lingkungan aktifis. Tapi kenapa, paska penembakan mahasiswa Tri Sakti, warga keturunan China diburu dan diperkosa, itu yang sampai sekarang mengganjal di benak saya.
Maka, dengan mencermati hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta terkait kerusahan 13 – 14 Mei 1998, saya berkesimpulan, kendati prasangka buruk tentang etnis China sudah menjadi pandangan umum sebagian warga, tapi tanpa adanya pemicu mustahil terjadi kerusuhan yang massif di kantong-kantong pemukiman yang banyak warga keturunan Chinanya. Kebanyakan warga paling hanya sampai sebatas melakukan penjarahan, sebagai pelampiasan dendam atas dugaan dikangkanginya ekonomi oleh warga keturunan China, tidak sampai ke kasus penganiayaan atau bahkan kasus-kasus perkosaan yang berdasarkan investigasi Kalyanamitra dan Tim Relawan Kemanusiaan banyak terjadi di Jakarta Barat.
Tapi, para pemicu kerusuhan yang dikabarkan didrop melalui truk, siapapun bos yang memberi perintah, tentu sudah melihat tanda-tanda jaman, bahwa ilalang kering itu siap disulut dan bila bisa dikendalikan, maka pengendalinya pasti didaulat menjadi pahlawan. Apa lagi bila memperhatikan fakta lapangan, seperti dugaan terjadinya pembiaran, minimnya personil yang diturunkan dalam pengamanan, membuat spekulasi yang beredar seperti pekerjaan intel sah-sah saja bila dianggap kebenaran. Sebab, hasil temuan TGPF sendiri hingga kini tidak ditindak-lanjuti oleh siapapun pemerintahan yang berkuasa, sehingga peristiwa mengenaskan dibiarkan tanpa penuntasan rasa keadilan.
Ilalang itu ternyata terbakar dan tak seorang pun mampu mengendalikan. Tak seorang pun menjadi pahlawan, seperti saat Soeharto mampu mengendalikan peristiwa 1965. Yang ada hanya tudingan, ada yang mengarah ke Prabowo dan ada yang mengarah ke Wiranto yang saat kejadian ada di Malang, Jawa Timur. Tapi semua tudingan itu masih sumir, karena tidak adanya kemauan politik siapapun pemerintahan yang berkuasa untuk menyeret siapapun yang diduga pelakunya ke mahkamah militer luar biasa.
Sayangnya, bukan ilalang saja yang terbakar, melainkan hampir semua sendi kehidupan, termasuk sikap saling percaya antara ras, agama, suku dan golongan yang sesungguhnya sudah terjalin, setidaknya di lingkungan aktivis gerakan sejak 1966. Bukankah dulu ada Sofyan dan Yusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi, atau (Alm) Soe Hok Gie dan kakaknya Arief Budiman. Di era 1980-an ada Andreas Harsono, ada Ariel Haryanto, ada Enin Supriyanto, ada Stanley alias Yosep Adi Prasetyo. Dan generasi saya dan sesudahnya ada Wiwil, Sisi, Esther Yusuf, dan Yun Hap yang gugur dalam Peristiwa Semanggi 24 September 1998, dan masih banyak lagi.
Kepercayaan itu dimusnahkan oleh peristiwa 13-14 Mei. Maka, perlu diapresiasi saat Esther Yusuf mendirikan Solidaritas Nusa Bangsa (SNB). Dengan berdirinya lembaga itu, saya berharap solidaritas kebangsaan perlahan-lahan pulih, terutama di kalangan keturunan China yang wajar saja bila hingga sekarang ada yang tampak menjaga jarak dengan kita-kita yang pribumi. (*)
Jakarta, 5 September 2011
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com




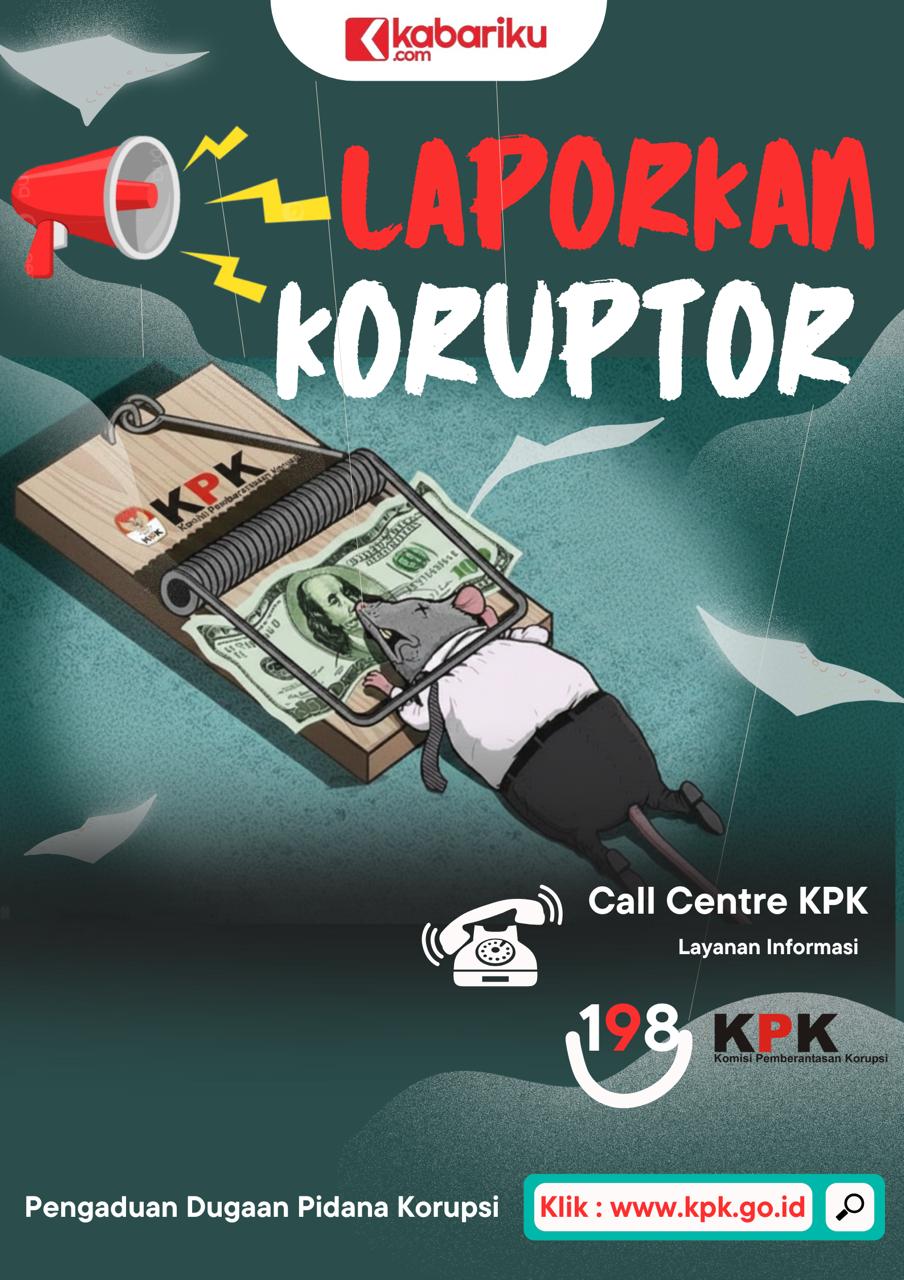


















Discussion about this post