Penulis :
Ahmad Faisal Ibrahim
Sekretaris Wilayah STN Jawa Barat
Jakarta, Kabariku – Di negeri yang mengaku berakar pada tanah dan bertumpu pada laut, petani dan nelayan tetap menjadi kelas yang paling dijauhkan dari ruang produksi yang seharusnya mereka kuasai.
Mereka dipuji sebagai penyedia pangan bangsa, dijadikan ikon dalam pidato-pidato seremoni negara, namun dalam praktiknya dibiarkan berjalan sendirian dalam belantara pertarungan modal.
Mereka dijanjikan kesejahteraan, tetapi dipasung oleh kebijakan yang sejak awal tidak disusun dari sudut pandang mereka. Mereka disebut tulang punggung, tetapi justru dipecah-pecah tulang punggungnya oleh sistem yang lebih menghargai sertifikat, bank, dan legalisasi aset ketimbang kedaulatan pangan.
Dalam Kongres ke-9 Serikat Tani Nelayan di Desa Kemitir, para petani dan nelayan mengutarakan keluh yang sama: bahwa mereka tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam, dan tidak memiliki wilayah tangkap untuk menebar jala.
Sebagian besar hanya menggarap, bukan menguasai. Mereka menggantungkan hidup pada tanah milik orang lain, laut yang semakin dipagari kebijakan, dan alat produksi yang harganya ditentukan oleh pasar yang tidak pernah berpihak.
Namun diatas semua itu, ada kegelisahan yang lebih dalam-kegelisahan yang muncul dari kontradiksi negara: di satu sisi negara mengatakan telah menjalankan reforma agraria, tetapi di sisi lain negara mengajarkan petani untuk mengagunkan tanahnya ke bank.
Inilah akar persoalan yang harus dituliskan dengan terang, tanpa tedeng aling-aling.
Tanah, Investasi, dan Tenaga yang Dinafikan: Modal yang Tidak Pernah Diberikan kepada Petani
Dalam teori ekonomi politik, modal terbagi dalam tiga bagian:
-Tanah yang menghasilkan sewa.
-Investasi yang menghasilkan laba.
-Tenaga manusia yang menghasilkan nilai.
Tetapi dalam praktik kehidupan sehari-hari, ketiganya justru terlepas dari tangan petani dan nelayan.
Tanah, alat produksi yang paling dasar, telah berubah menjadi komoditas pasar. Ia diperjualbelikan, dijadikan jaminan kredit, atau masuk ke dalam skema konsesi yang lebih menguntungkan perusahaan besar. Petani dipaksa menyewa tanah yang seharusnya menjadi “ruang hidup”.
Investasi, alat untuk meningkatkan produktivitas, justru dikuasai pemodal luar desa. Rice mill, mesin kapal, cold storage, hingga mesin pengering gabah lebih banyak dimiliki mereka yang tidak berkeringat di sawah atau di laut.
Laba mengalir keluar desa, bukan kembali ke koperasi tani dan nelayan.
Tenaga manusia, nilai kerja petani dan nelayan, dihargai murah. Petani musiman dibayar harian, nelayan kecil menjadi ABK dalam sistem bagi hasil yang timpang, sementara perusahaan perikanan besar memborong hasil tangkap lewat skema harga yang ditentukan sepihak.
Dalam struktur seperti ini, petani dan nelayan diletakkan sebagai pengabdi produksi, bukan sebagai pemilik produksi.
Laut sebagai “Tanah Air”: Ruang Produksi yang Diprivatisasi Negara
Laut adalah tanah air yang sesungguhnya—ruang hidup, ruang produksi, ruang budaya. Namun laut telah memasuki babak baru: babak privatisasi.
Zonasi laut, kawasan industri pesisir, kawasan konservasi yang tidak melibatkan nelayan, konsesi perusahaan, hingga praktik penangkapan skala besar yang menghabiskan stok ikan-semuanya membuat nelayan kehilangan wilayah tangkap yang sejak lama menjadi tradisi.
Negara membangun pelabuhan industri, namun menarik garis untuk membatasi nelayan kecil.
Negara melarang alat tangkap tertentu, tetapi membiarkan perusahaan besar beroperasi dengan teknologi yang lebih ganas.
Negara bicara ekologi, tetapi tidak memberi ruang bagi masyarakat pesisir untuk mengatur wilayah kelolanya sendiri.
Padahal laut, sebagaimana tanah, memiliki potensi sebagai sumber sewa komunitas.
Jika nelayan diberi hak kelola-bukan hak formal yang mati di atas kertas, tetapi hak yang hidup dalam praktik harian-maka mereka dapat membangun sistem tangkap eksklusif, sea farming, pariwisata bahari berbasis komunitas, hingga tambat labuh yang dikelola bersama.
Laut bukan ruang kosong. Ia adalah ruang produksi yang seharusnya dibagi bersama mereka yang hidup darinya.
Kontradiksi Negara: Reforma Agraria yang Berjalan Mundur
Selain persoalan tanah dan laut, satu hal yang paling menyakitkan dalam logika agraria hari ini adalah kontradiksi yang muncul dari pemerintah sendiri, khususnya aparatur ATR/BPN.
Dalam banyak kesempatan resmi, pejabat ATR/BPN menyatakan bahwa:
“Setelah petani menerima sertifikat, sertifikat itu bisa diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal.”
Pernyataan ini, yang diucapkan dengan penuh kebanggaan birokratis, sesungguhnya menyimpan jebakan struktural.
Pertama, ia menempatkan tanah sebagai objek kredit, bukan alat produksi.
Kedua, ia menjerumuskan petani ke dalam mekanisme utang yang penuh risiko.
Ketiga, ia membuka pintu lebar bagi terjadinya penyitaan apabila petani gagal membayar cicilan.
Jika tanah sudah bisa disita bank, apa bedanya negara Indonesia hari ini dengan praktik kolonial yang mengeksploitasi tanah rakyat?
Inilah kontradiksi paling telanjang dari kebijakan agraria modern: negara mengaku menjalankan reforma agraria, tetapi memberikan instruksi yang berpotensi mencabut kembali tanah dari tangan petani.
Reforma agraria sejati tidak mungkin terwujud bila tanah diubah menjadi agunan kredit. Reforma agraria sejati tidak lahir dari logika perbankan.
Dan reforma agraria sejati tidak akan pernah berjalan selama negara gagal memahami dialektika petani: bahwa tanah adalah ruang hidup, bukan aset keuangan.
Dialektika Petani: Pengetahuan yang Tidak Pernah Diajarkan di Balai Diklat Negara
Dialektika petani tidak lahir dari ruang kuliah atau kelas pelatihan pejabat. Dialektika itu lahir dari tanah yang diayun cangkul, dari laut yang ditembus perahu, dari tubuh mereka sendiri yang memikul beban produksi.
Mereka tahu, tanpa perlu membaca teori, bahwa:
-Bila tanah dikuasai bersama, maka sewa kembali kepada komunitas.
-Bila alat produksi dimiliki koperasi, maka laba kembali ke kelompok, bukan ke tengkulak.
-Bila nilai kerja dihargai dengan adil, maka upah dan bagi hasil membangun massa rakyat, bukan memperkaya perantara.
-Bila laut dijadikan wilayah kelola bersama, maka ikan tidak habis dan nelayan tidak terusir.
Mereka memahami bahwa kedaulatan pangan bukan soal sertifikat, melainkan soal kuasa atas ruang hidup. Bahwa reforma agraria bukan soal legalitas, tetapi soal siapa yang menentukan masa depan produksi pangan.
Dan mereka paham satu hal yang sangat fundamental:
bahwa negara tidak boleh berdiri sebagai pengantar kredit; negara harus berdiri sebagai penjamin alat produksi rakyat.
Meluruskan Arah Negara: Dari Logika Bank ke Logika Rakyat
Negara hari ini berjalan dengan logika yang berseberangan dengan rakyat. Negara menggunakan logika bank: bahwa aset harus disertifikasi, diukur, dinilai, dan disiapkan untuk dipinjamkan. Padahal rakyat berjalan dengan logika hidup: bahwa tanah dan laut adalah ruang produksi, bukan barang gadai.
Jika negara ingin dianggap berpihak, maka negara harus meninggalkan logika bank itu dan kembali ke logika rakyat.
Itu berarti:
-Tanah tidak boleh lagi dijadikan agunan kredit.
-Laut tidak boleh diprivatisasi melalui zonasi yang tidak demokratis.
-Koperasi harus diposisikan sebagai organisasi produksi, bukan sekadar formalitas administrasi.
-Reforma agraria harus mengutamakan redistribusi, bukan legalisasi.
Negara harus belajar dari petani dan nelayan, bukan sebaliknya.
Tanah untuk Petani, Laut untuk Nelayan, Negara untuk Rakyat
Perjuangan petani dan nelayan di Desa Kemitir bukan sekadar keluh, tetapi seruan untuk meluruskan arah negara. Seruan bahwa:
-Tanah tidak boleh lagi menjadi objek perampasan baru melalui skema kredit.
-Laut tidak boleh lagi menjadi wilayah yang hanya dapat dinikmati pemodal besar.
-Reforma agraria tidak boleh diperkecil menjadi proyek sertifikasi massal.
-Kedaulatan pangan tidak akan pernah terwujud tanpa alat produksi di tangan rakyat.
Negara yang benar adalah negara yang melihat petani dan nelayan bukan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek sejarah. Sebagai kelas yang mengetahui dengan pasti apa yang mereka perlukan untuk hidup.
Dan selama negara belum memahami itu, selama tanah masih dijadikan agunan, selama laut masih dibatasi tanpa suara nelayan, maka perjuangan harus terus berjalan.
Karena sebuah bangsa tidak mungkin berdiri tegak bila tanahnya tidak di tangan petani dan bila lautnya tidak di tangan nelayan.***
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com




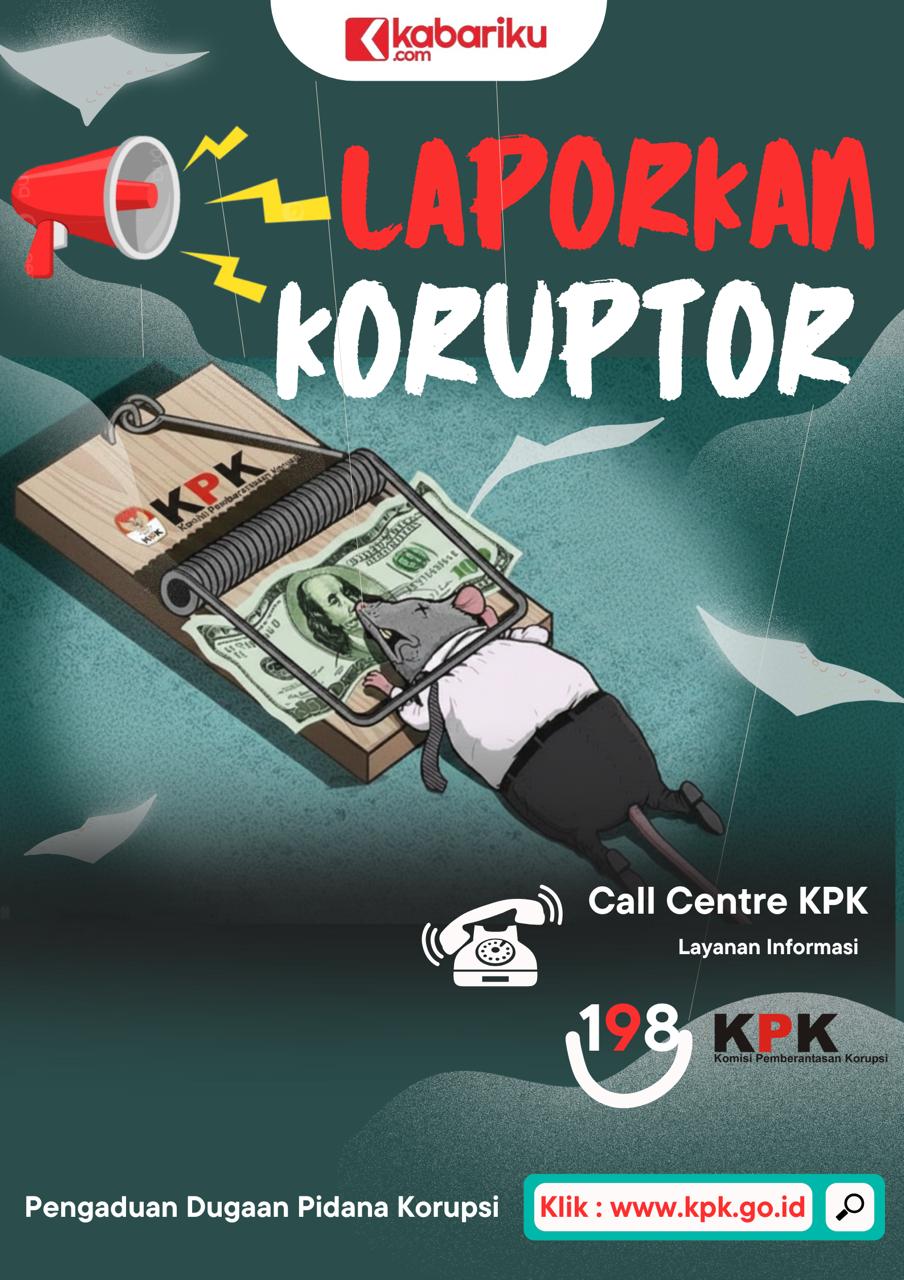



















Discussion about this post